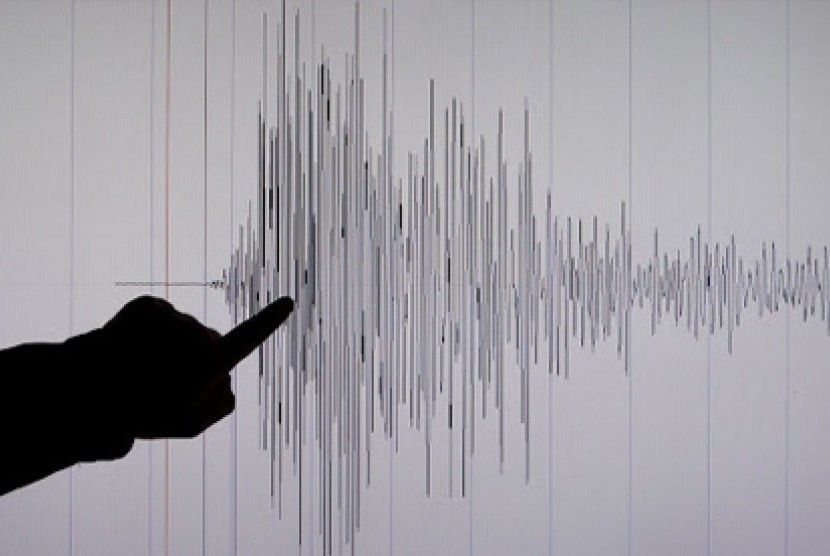(Dok. Pribadi)
(Dok. Pribadi)
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia. Editorial tersebut mengingatkan dugaan skandal beras oplosan tidak boleh dianggap sebagai insiden sesaat sehingga mesti segera diakhiri.
Praktik oplosan dan manipulasi pangan tak hanya terjadi di Indonesia, tak hanya pada beras, dan tak hanya soal untung-rugi. Dunia pernah dan sedang berhadapan dengan skandal serupa, yang memukul tidak hanya industri pangan, tapi juga kesehatan publik dan keberlanjutan sistem pangan itu sendiri.
Pada 2013, Eropa diguncang skandal daging kuda (horse meat scandal) yang mana produk olahan seperti lasagna, burger, dan produk serupa yang diklaim sebagai daging sapi ternyata mengandung daging kuda. Jejaring perusahaan multinasional terlibat dalam skandal ini.
Tiongkok mengalami insiden lebih tragis. Pada 2008, pemerintah membongkar skandal pencampuran susu formula bayi dengan melamin untuk memalsukan kadar protein. Akibatnya, puluhan ribu bayi mengalami gagal ginjal, bahkan enam meninggal dunia. Industri susu domestik runtuh.
Di Indonesia, praktik mengoplos atau memanipulasi pangan tidak hanya terjadi di distributor besar, tetapi juga diduga sudah di tingkat produsen hulu hingga pedagang kecil. Misalnya, ayam broiler disuntik air untuk menambah berat atau susu sapi dicampur bahan lain untuk menambah volume.
RENTAN DI SEMUA LINI
Benang merah dari beberapa kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aksi mengoplos dan memanipulasi pangan tidak mengenal negara dan level distribusi. Negara maju atau negara berkembang juga rawan dengan aksi ini. Pedagang kecil atau industri juga rentan jadi pelaku.
Lantas, apa yang mendasari perilaku tersebut? Apa pun komoditasnya, daging, susu, hingga beras, terdapat pola yang hampir serupa, yakni mengejar margin keuntungan dari penambahan kuantitas (berat atau volume) atau kualitas (grade atau mutu).
Dari margin keuntungan yang didapat, banyak hal dikorbankan di sini. Mulai risiko kontaminasi, harga pasar yang rusak, hingga kepercayaan publik yang menurun. Petani dan pelaku usaha yang jujur akan terpukul. Konsumen juga dirugikan dengan kualitas pangan yang tak transparan.
Konteks keberlanjutan juga mengingatkan kita pada dimensi lingkungan dan kesehatan yang sering terabaikan. Aksi mengoplos atau memanipulasi pangan tentu akan mengabaikan standar lingkungan, kesehatan, hingga hak-hak hewan ternak.
Dengan kata lain, dampak dari pangan oplosan dan manipulatif bukan hanya soal siapa memakan apa, melainkan juga soal bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Tentu akan ada kerugian ekologi dan ekonomi di balik hal tersebut.
RESPONS KOLEKTIF
Lantas, bagaimana seharusnya kita merespons? Pengawasan dan tindakan hukum yang ketat memang mutlak diperlukan, tetapi yang lebih mendasar ialah membangun ekosistem pangan yang adil dan transparan.
Pertama, pembenahan harus dimulai dari sisi hulu, petani kecil harus diperkuat posisinya agar mereka tidak terdorong memanipulasi produk demi mengejar keuntungan tipis. Dukungan kepada petani dapat berupa pemberlakukan harga jual yang layak dan akses pembiayaan.
Kedua, dari sisi distribusi, sistem pelacakan dan sertifikasi produk harus diperkuat. Banyak negara telah menggunakan teknologi, seperti QR code atau blockchain untuk memastikan jejak asal-usul pangan dapat dilacak hingga ke tangan konsumen. Tentu layak untuk diterapkan secara luas di Indonesia.
Ketiga, dari sisi hilir, literasi konsumen memegang peran penting. Konsumen berhak mengetahui kualitas produk yang mereka beli, bukan hanya harga, melainkan juga dari mutu. Edukasi tentang hak-hak konsumen dan identifikasi produk bermasalah, bisa menjadi alat pemberdayaan yang efektif.
Yang tak kalah penting ialah memandang isu ini dalam kerangka sistem pangan dan keberlanjutan. Praktik pangan oplosan dan manipulatif di hilir dapat mematikan motivasi petani dalam memproduksi beras berkualitas dan peternak untuk memproduksi daging yang sehat dan ramah lingkungan.
Petani dan peternak yang berupaya menerapkan praktik berkelanjutan justru sering kalah saing dengan produk murah yang manipulatif. Di sisi lain, konsumen yang mestinya menjadi mitra dalam rantai pangan justru dirugikan dan kehilangan akses pada informasi pangan yang transparan
Keberlanjutan pangan bukan hanya soal meningkatkan produksi, melainkan juga soal menciptakan keadilan di sepanjang rantai nilai, dari petani hingga konsumen, dari lahan hingga meja makan. Praktik mengoplos pangan bukan sekadar soal etika dagang, melainkan juga cerminan rapuhnya sistem pangan kita.
Yang juga penting ialah membangun narasi bahwa keberlanjutan pangan ialah tanggung jawab kolektif. Konsumen bisa memilih lebih bijak, produsen perlu lebih bertanggung jawab, regulator perlu mendorong praktik yang adil, hingga akademisi dan peneliti menghadirkan inovasi berbasis bukti.
Membenahi masalah ini artinya memperkuat semua lini, dari petani hingga peternak, dari pasar hingga piring rakyat. Hanya dengan begitu kita bisa memastikan bahwa pangan yang sampai ke masyarakat tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyehatkan dan bermartabat.

 21 hours ago
3
21 hours ago
3